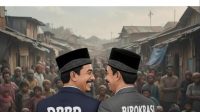Oleh: Gus Imam (Pengasuh Ponpes Raden Patah Magetan)
BeritaTrends, Magetan – Ada saat ketika sejarah tidak sekadar dibaca, tetapi dirasakan sebagai denyut ruh bangsa. Itulah makna 28 Oktober 1928 — ketika sekelompok pemuda berhimpun dalam Kongres Pemuda II, menulis tiga kalimat yang mengguncang waktu: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Di bawah langit yang mungkin sederhana, lahir sebuah kesadaran luar biasa: bahwa persatuan adalah fondasi eksistensial bangsa ini.
Namun kini, hampir satu abad kemudian, kita berdiri di simpang zaman. Era digital menyalakan dunia, tetapi juga menenggelamkan nurani. Nilai menjadi cair, orientasi moral kabur, dan syakhshiyyah (kepribadian) pemuda Indonesia kerap terombang-ambing antara euforia modernitas dan kehampaan spiritual. Maka, peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2025 seharusnya bukan sekadar seremoni nasional, melainkan muhasabah — refleksi ruhani, sosial, dan intelektual bangsa.
Data empiris yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 mengingatkan kita tentang kenyataan yang tak bisa disembunyikan. Jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76%. Lebih menyedihkan, kelompok usia muda (15–24 tahun) menyumbang 16,16% dari total pengangguran nasional. Artinya, satu dari enam pemuda Indonesia hidup dalam ketidakpastian masa depan.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat angka putus sekolah tahun ajaran 2024/2025 masih tinggi: 38.540 siswa SD, 12.210 siswa SMP, 6.716 siswa SMA, dan 9.391 siswa SMK. Setiap angka bukan sekadar statistik, tetapi potret cita-cita yang patah — impian yang tak sempat mekar karena jerat kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan.
Sementara itu, Survei Nasional Kesehatan Mental Remaja (I-NAMHS) menunjukkan bahwa 15,5 juta remaja Indonesia (34,9% populasi usia 10–17 tahun) mengalami gangguan mental — mulai dari kecemasan, depresi, hingga kehilangan makna hidup. Ini bukan sekadar masalah psikologis, tetapi spiritual vacuum, kekosongan makna yang lahir ketika generasi kehilangan orientasi ruhani dalam hidupnya.
Fenomena ini menuntut pembacaan lebih dalam. Dalam perspektif tasawuf, krisis pemuda hari ini bukan sekadar krisis ekonomi, tetapi krisis ruh al-jihad — semangat juang yang berpijak pada kesadaran ilahiyah. Sebab, pemuda yang kehilangan ruh spiritual akan kehilangan arah perjuangan: mungkin aktif, tapi tanpa makna; produktif, tapi tanpa nilai.
Ada empat faktor penyebab utama.
Pertama, educational mismatch antara sistem pendidikan dan dunia kerja. Banyak lulusan muda tidak memiliki employability skill yang relevan. Laporan Bank Dunia 2025 menunjukkan hanya 48% lulusan vokasi terserap kerja dalam enam bulan. Pendidikan kehilangan ruh ta’dib — fungsi membentuk adab dan kompetensi sekaligus.
Kedua, ketimpangan ekonomi struktural. Ribuan anak harus meninggalkan sekolah untuk membantu keluarga. Kemiskinan menjerat bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena tidak adanya ruang untuk tumbuh.
Ketiga, psychological disorientation akibat derasnya arus digital. Pemuda hidup di tengah noise informasi yang berlimpah, namun kehilangan inner voice. Mereka hidup di dunia yang sibuk berbicara, tapi jarang mendengar.
Keempat, lemahnya sistem sosial dan spiritual yang menopang karakter pemuda. Ketika agama hanya diajarkan sebagai pengetahuan kognitif, bukan kesadaran eksistensial, lahirlah generasi yang tahu Tuhan tetapi tidak merasa diawasi oleh-Nya (murâqabah).
Namun, dalam setiap krisis tersimpan potensi kebangkitan. Crisis is not the end — it is the threshold of transformation.
Indonesia memiliki bonus demografi luar biasa: 52% penduduk berusia di bawah 35 tahun. Mereka adalah energi perubahan yang bila dikelola dengan visi dan spiritualitas, dapat menjadi motor civilizational renewal. Ledakan ekonomi digital juga membuka ruang bagi kreativitas dan entrepreneurial mindset. Tahun 2025, Indonesia mencatat lebih dari 2.500 startup, kelima terbanyak di dunia.
Tetapi ada pula faktor penghambat: policy fragmentation lintas kementerian, digital divide (22% wilayah minim internet), stigma terhadap kesehatan mental, serta moral crisis — krisis keteladanan publik yang membuat anak muda kehilangan figur inspiratif.
Lalu apa yang harus dilakukan?
Pertama, pendidikan harus direformulasi menjadi wahana tazkiyah (penyucian jiwa) sekaligus ta’dib (pembentukan adab). Keterampilan penting, namun adab adalah pondasi. Rasulullah ﷺ bersabda: “Innamâ bu‘itstu li utammima makârimal akhlâq” (Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia) — HR. Ahmad.
Kedua, bangun sistem link and match antara pendidikan dan industri. Program “Skill to Job” mesti berbasis competency-based learning dan paid internship, menargetkan penurunan TPT pemuda dari 16,16% ke <12% dalam tiga tahun.
Ketiga, bentuk National Mental Health Ecosystem. Setiap sekolah wajib punya counseling center dan peer-support program dengan target menurunkan prevalensi gangguan mental dari 34,9% ke 25% dalam lima tahun.
Keempat, dorong entrepreneurial empowerment melalui program “10.000 Youth Startup” yang berkelanjutan — bukan sekadar proyek politik. Pemuda harus dilatih menjadi job creator, bukan hanya job seeker.
Kelima, bangun spiritual consciousness atau ma‘rifah al-nafs — kesadaran mengenal diri untuk mengenal Tuhan. Imam al-Ghazali menulis, “Man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa Rabbahu” (Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya). Hanya pemuda yang mengenal hakikat dirinya yang akan menemukan misinya dalam kehidupan.
Tema resmi pemerintah tahun ini, “Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh untuk Indonesia Emas 2045,” harus dibaca bukan sekadar slogan politik, tetapi sebagai moral imperative. “Bersatu” bermakna menyatukan dimensi lahir dan batin bangsa; “Bangkit” seruan membangunkan potensi ruhani yang tertidur; dan “Tumbuh” berarti menghidupkan budaya ilmu, etos kerja, dan spiritualitas publik.
Kita tidak sedang kekurangan kecerdasan, tetapi kekurangan kesadaran. Yang hilang bukan knowledge, tetapi wisdom. Kita kaya data, tetapi miskin makna. Refleksi Sumpah Pemuda 2025 harus diarahkan pada epistemic awakening — kebangkitan kesadaran ilmu dan iman.
Pemuda sejati bukan mereka yang hanya viral, tetapi visionary; bukan yang mempercantik profil digital, tetapi yang memperbaiki realitas sosial. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ: “Khairunnâs anfa‘uhum linnâs” — sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya (HR. Ahmad).
Kini, di usia ke-97 tahun Sumpah Pemuda, bangsa ini tidak lagi menunggu orator besar, tetapi pemuda yang berpikir, berzikir, dan bertindak; yang memiliki intellectual integrity dan spiritual depth; yang menjadikan tauhid bukan sekadar doktrin, tapi paradigma berpikir.
Bangkitlah wahai generasi 2025. Jadilah agent of transformation yang membawa cahaya, bukan sekadar suara; berpikir global namun berhati lokal; melek teknologi namun berakar pada moralitas ilahiyah. Jadilah pemuda yang menulis sejarah, bukan sekadar membaca sejarah.
Sebagaimana firman Allah:
“Inna Allâha lâ yughayyiru mâ biqawmin hattâ yughayyirû mâ bi-anfusihim” — Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra‘d: 11).
Dan perubahan itu — perubahan sejati — dimulai bukan dari dunia luar, tetapi dari hati yang menyala oleh iman, ilmu, dan cinta tanah air.
Maka, pada peringatan Sumpah Pemuda 2025 ini, mari kita hidupkan kembali ruhnya: bukan sekadar satu bangsa dan satu bahasa, tetapi satu ruh al-jihad untuk menegakkan peradaban. Karena sumpah itu bukan hanya diucapkan, tapi diwariskan — melalui kerja, akhlak, dan doa.
Sumpah Pemuda bukan sejarah yang lewat. Ia adalah amanah yang hidup — dan kini, ada di tangan kita.